Judul buku : Affandi Pelukis
Penulis : Nasjah Djamin
Penerbit : Aqua Press Bandung
Jumlah halaman : 84
Nilai : 3 dari 5
Satu lagi buku yang
masuk kategori “buku cerita” hasil proyek Depdikbud zaman Soeharto. Aku
sebutkan di awal karena diam-diam out of
nowhere buku ini menjejalkan pujian kepada Soeharto, presiden ketika itu,
pada pertengahan buku di saat membicarakan Affandi.
“Anak desa pun dapat jadi orang,
asal rajin dan tekun belajar. Anak desa pun kelak dapat menjadi Menteri, jadi
Jenderal, malah jadi Presiden. Seperti halnya Pak Harto, Presiden Negara
Republik Indonesia kita yang sekarang!” (Djamin,
1979:44).
Dan, lagi-lagi tipe
karangan buku ini persis seperti buku cerita lain yang sudah kuulas sebelumnya
di blog ini: Ada sub-plot tokoh utama abal-abal dibangun menuju tokoh utama
sebenarnya, dalam hal ini Affandi, namun sub-plot ini posisinya kurang penting
walau bukannya tidak relevan atau tidak relatable.
Karena setidaknya tokoh sub-plot ini punya latar dan kepribadian.
Pada mulanya kita diperkenalkan
kepada seorang anak petani yang masih duduk di kelas 6 SD bernama Agus. Dia tinggal
di desa Besi (baca: mbesi) di sekitaran Jalan Kaliurang Yogyakarta. Bakat
menggambarnya mengagumkan sehingga suatu kali gurunya memujinya bahwa dia bisa
seterkenal Affandi sang pelukis. Dari situ rasa penasaran dan kagum Agus kepada
Affandi tumbuh.
Suatu hari pamannya
(yang tanpa nama) datang, dia mengajak Agus berkunjung ke Museum Affandi
berboncengan naik sepeda motor butut. Setidaknya kita mendapat gambaran seperti
apa suasana Jogja akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an (buku ini pertama kali
terbit 1977) yang terasa sangat syahdu: kala itu penduduk desa naik cikar (gerobak
sapi) ke kota untuk plesiran, jika tidak ya naik bus atau colt yang mulai banyak
mondar-mandir dari Yogyakarta-Kaliurang (Djamin, 1979:19). Pemandangan yang sudah
lenyap hari ini.
Tapi sayang eh sayang museumnya
sedang tutup karena Pak Affandi sedang pergi melukis di Bali. Tuh kan
sub-plotnya bertele-tele. Kunjungan dibatalkan, mereka kemudian berbelok ke
kos-kosan (disebut pondokan) si Paman dan bertemu dengan [Jeng] Juminten, teman
(pacar?) Si Paman. Dia adalah seorang pengarang amatir yang secara kebetulan
sedang menulis tentang Affandi. Draf tulisan berjudul “Pelukis Besar Affandi” ini kemudian dibaca oleh Agus (alias kita)
dan baru muncul di halaman 33 (hingga 78) dari total 84 halaman!
Membaca draf tulisan
Juminten bagai membaca biografi a la Wikipedia.
Ringkas, padat, dan seolah tidak ada penyuntingan atas tata kalimat, bahkan urutan
peristiwanya meloncat-loncat. Sehingga terbitlah kecurigaanku bahwa draf tulisan
ini memang tulisannya ‘Juminten’ sungguhan (maksudnya Juminten benar-benar ada).
Mungkin dia temannya Djamin, penulis buku ini.
Inti cerita kurang
lebih berkutat pada kerasnya hidup yang dijalani Affandi hingga sukses dikenal sebagai
pelukis tetapi tetap bersahaja. Kita diperkenalkan pada masa kecil Affandi yang
sudah hobi menggambar. Ayah dan saudara-saudaranya memang menentang hasrat
melukis Affandi tersebut, namun dia berhasil membuktikan bahwa dia bisa menghidupi
diri, anak, dan istrinya dari hasil melukis setahap demi setahap. Mulanya tentu
tidak mudah, sekolah sengaja dia tinggalkan, pekerjaannya pun serabutan, mulai
dari guru, tukang cat, penggambar poster reklame, sampai penjaga pintu bioskop sambil
terus melukis meskipun tidak kunjung laku.
Keinginannya untuk belajar
melukis di sekolah khusus gambar tidak pernah kesampaian. Sempat dia ingin
berguru kepada Basuki Abdullah tetapi pelukis terkenal itu tidak berkenan. Affandi
kemudian bergabung di Persagi (Persatuan Ahli Gambar Indonesia) yang terdiri
dari pelukis-pelukis yang tidak diakui oleh Belanda karena mereka hanya pelukis
otodidak.
Di masa pendudukan
Jepang, Affandi bergabung dengan PUTRA (Pusat Tenaga Rakyat) lalu ikut pula dalam
SIM (Seniman Muda Indonesia). Di sana dia mulai melukis keadaan rakyat yang melarat
dan menderita: romusha yang tubuhnya kurus kering, gelandangan, kuda andong yang
kurus, pedagang pasar yang dekil. Dia juga maju ke medan perang untuk melukis
suasana pertempuran.
Ketika agresi militer
Belanda pecah, Affandi sekeluarga mengungsi ke Jakarta. Di kota yang diduduki
Belanda dia tinggal di sebuah garasi di Perguruan Taman Siswa, satu dari wilayah
RI di Jakarta selain Gedung Proklamasi (data sejarah bung! RI masih punya
wilayah di tengah kekuasaan Belanda). Di situlah dia berjumpa dan melukis Chairil
Anwar.
Sesudah kemerdekaan
Affandi mendapat beasiswa di sebuah sekolah seni di India. Begitu sampai pihak
kampus menilai bahwa kemampuan Affandi sudah sempurna sehingga tidak perlu
sekolah lagi. Dia memutuskan untuk berkeliling kota-kota India lanjut ke Eropa sambil
terus melukis. Dari sini namanya mulai dikenal publik.
Sekembalinya ke Indonesia,
dia ditawari mengajar di ASRI Yogyakarta dan berpameran di Jepang, Brasil,
Meksiko, dan Amerika. Di negara yang disebut terakhir ini dia sempat menjadi profesor
di Ohio State University. Dari hasil menjual lukisannya dia membangun Museum
Affandi di tepi kali Gajahwong. Seperti tema yang senantiasa berulang: kesusahan,
keterlunta-luntaan, dan kehinaan yang dialami tokoh utama pun berbuah manis. SELESAI.
Seusai membaca draf
tulisan Jum, Si Agus bertandang ke Museum Affandi dan menyimak deskripsi beberapa
lukisan via mulut pamannya dan Mbak Jum. Tentu tidak lupa untuk bertemu langsung
dengan idolanya tersebut dan mendapat wejangan: “Yang rajin belajar seperti kakek ini. Sudah tua masih belajar, dan
ingin belajar terus!”
 |
| halaman terakhir yang berisi pesan Affandi kepada kita |
Iya, iya. Agus harus rajin
belajar sampai tua. KITA pun harus terus belajar sampai tua.
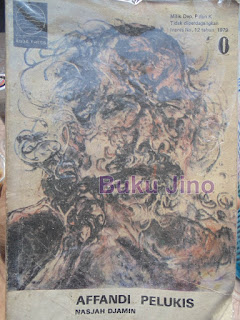





0 komentar:
Posting Komentar